Integritas Penelitian Indonesia: Refleksi Oportunisme Institusi dan Peneliti

13 kampus di Indonesia masuk daftar RI2 (Research Integrity Risk Index), 5 di antaranya masuk kategori red flag (extreme anomalies). Apakah ini adalah tanda bahwa integritas penelitian Indonesia sudah mulai hilang? Atau justru sudah hilang?
Menariknya, kampus-kampus yang masuk daftar “beresiko” RI2 itu bukan kampus-kampus yang “B-aja”. Tapi kampus besar yang sering diklaim “terbaik”, “terbesar”, dan ter-ter-ter lainnya.
Melihat data dari RI2, orang awam pun bahkan saja bisa berpikir gini, “Lha wong yang besar aja gitu, apalagi yang kecil?”
Research Integrity Risk Index
Meski baru, saya rasa RI2 memiliki metodologi yang cukup kuat. Pengembang RI2 adalah Profesor Lokman Meho dari American University of Beirut. Beliau mengembangkan RI2 karena kekhawatiran atas integritas penelitian ilmiah yang dikorbankan hanya untuk memaksa pemeringkatan universitas lewat publikasi.

Singkatnya, RI2 menghitung integritas penelitian universitas di dunia dengan pertimbangan:
- Penarikan artikel jurnal: karena fabrikasi, plagiarisme, pelanggaran etika, manipulasi, dan kecacatan metodologis).
- Delisting Scopus dan WoS: penelitian universitas yang ada di jurnal-jurnal discontinued Scopus dan Web of Science.
- Sitasi mandiri (peneliti melakukan sitasi pada penelitiannya sendiri)
Beberapa aspek tersebut dilakukan perhitungan secara intensif dan skornya (0-1) diklasifikasikan (tier) menjadi 5 kelompok universitas:
- Red flag (Penyimpangan ekstrem, risiko integritas ekstrem)
- High Risk (Penyimpangan yang signifikan)
- Watch List (Risiko penyimpangan tinggi, mengkhawatirkan)
- Normal Variation (Normal, tidak berisiko)
- Low Risk (Patuh dan taat norma integritas penerbitan)
Saya yakin “pasti” ada kekurangan metodologi di balik RI2, mungkin dari sisi perhitungan, pengelompokan bidang, periode pengambilan sampel, atau bahkan interpretasi.
Maka sangat wajar bila ada peneliti lain yang meragukan, skeptis, atau bahkan menolak sama sekali; khususnya karena reputasi lembaga yang menaungi RI2, subjektivitas penulis, dan lain-lain. Terlepas dari semua itu, RI2 adalah produk ilmiah yang patut menjadi alat refleksi atau peninjauan ulang regulasi kampus di negeri kita.
Tentu saja, kita tidak boleh 100% percaya, tidak pula 100% menolak. Harus tetap kritis terhadap informasi apapun—meskipun itu merupakan output dari penelitian ilmiah.
Pengaruh RI2 Terhadap Kampus Indonesia
Bayangkan, saat kampus berlomba-lomba mencitrakan diri baik, keren, berprestasi, dan layak untuk dimasuki, tiba-tiba RI2 datang dan mencoreng klaim-klaim itu. Maka saya yakin, pihak-pihak “kampus yang bersangkutan” mungkin akan meluangkan sedikit waktunya untuk klarifikasi (minimal ke mahasiswanya sendiri) atau mungkin saja tak acuh, “Heleh, biarin aja.”
Peduli atau tidak, RI2 pasti menggetarkan hati birokrasi kampus yang bersangkutan. Tidak hanya birokrasi, mahasiswa dan alumninya kemungkinan juga speak up—ada yang menolak RI2, ada juga malah ikut mempertanyakan integritas kampusnya.
Pada dasarnya, secara kuantitatif perangkingan RI2 tidaklah berpengaruh apa-apa terhadap universitas. Hanya saja, secara kualitatif—citra, nama baik, dan reputasi—bisa saja sedikit tercoreng. Namun bila kampus yang disebut RI2 adalah ITB, UI, UGM, IPB, ITB di kategori Watch List, saya yakin tidak ada efek apapun.
“Anggapannya gini: Ya sudah jadi risiko, banyak publikasi ya bisa saja banyak yang terdeteksi metriknya RI2. Yang jelas, publikasi kampus terbukti banyak kan?”
Dampak mungkin akan sedikit dirasakan oleh kampus yang masuk kategori red flag, seperti Binus University, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sebelas Maret. Rasanya, mereka seperti dituding sebagai kampus yang penelitiannya “nggak bener” dengan banyaknya publikasi riset yang tidak wajar. Tapi nggak tahu juga sih…
“Btw, ini bisa menjadi topik penelitian yang menarik. Efek RI2 terhadap citra kampus. Penggalian perspektif sivitas akademika kampus yang diklaim Red Flag, High Risk, dan Watch List versi RI2.”
Refleksi dan Berbenah
Selama dua dekade terakhir, integritas penelitian dalam skala dunia memang dinilai menurun (Armond dkk., 2024)1. Di tahun 2023 saja, lebih dari 10.000 artikel ilmiah ditarik karena melanggar; sebuah rekor baru (Noorden, 2023)2.
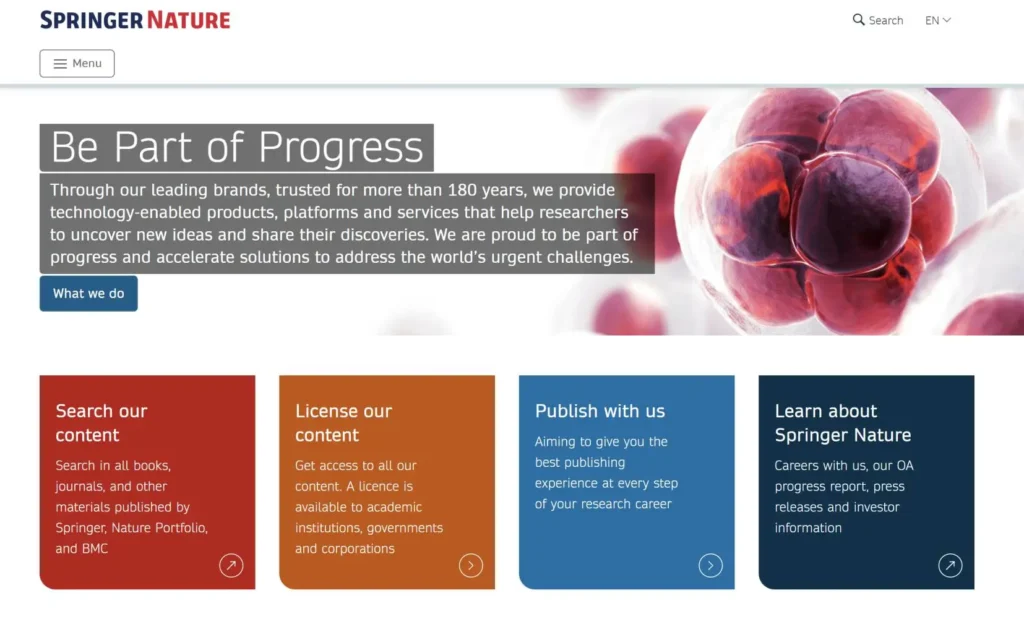
Dalam jurnal-jurnal terbitan Springer Nature (penerbit ilmiah bereputasi), ada 3000 makalah ditarik dari penerbitan di tahun 2024. Ini serius! Bayangkan, sebagian besar dari artikel ilmiah tersebut open-access, sudah dirujuk, dan dijadikan pondasi artikel-artikel lainnya. Tentu saja ada efek domino yang menyebabkan bias pada penelitian-penelitian lainnya.
Jangan jauh-jauh ke Springer, saya sendiri menemukan jurnal yang terbitannya di luar nalar tahun lalu. Baca artikel saya tentang: Kritik publikasi jurnal yang berlebihan.
Meski tidak bermaksud mendukung temuan RI2, apa yang saya temui di lapangan membuat saya yakin, RI2 sepertinya tidaklah salah. Praktik manipulasi data, oportunisme penelitian, plagiarisme, dan pelanggaran-pelanggan lain terhitung cukup wajar dilakukan di kampus-kampus yang saya pernah temui (dari pengalaman sendiri atau wawancara ke beberapa teman).
Ditambah ketika melihat negara teratas di rangking RI2 seperti India, Bangladesh, Saudi Arabia, Pakistan, China, dan Indonesia tercinta. Saya kok tambah yakin gitu 😄✌️.
1. Ekosistem Publikasi yang “Sakit”

Pemegang peran kunci ekosistem penelitian yang baik adalah institusi (Begley dkk., 2015)3. Sebenarnya sih institusi dan individu, namun melihat kondisi Indonesia, pendekatan top-down kami nilai lebih cocok, sebab kebanyakan individu “ngikut aturan” institusi.
Bukti ekosistem sakit antara lain adalah institusi terlalu mengejar jumlah publikasi dan sitasi, sehingga publikasi digas pol-polan dengan “memaksa” dosen-dosen untuk menerbitkan artikel ilmiah. Selain itu, institusi tidak terlalu care terhadap ethical clearance, kurang peduli pada aspek honestly dalam penelitian.
Dua poin besarnya adalah: (1) institusi terlalu fokus pada jumlah publikasi; dan (2) peneliti butuh dana dari institusi untuk penelitian dan “ambil bagiannya”. Saat dua poin ini masih berjalan selaras, percayalah integritas penelitian akan tetap mahal. Dosa-dosa penelitian akan terus dilakukan (Conroy, 2019)4.
Laporan dari RI2 tidak boleh dinilai sebagai olok-olok, tuduhan, atau fitnah. Institusi seperti universitas atau lembaga riset ilmiah di Indonesia harus refleksi—ngaca. Jangan menutup mata dan tak acuh. Regulasi penelitian harus ditinjau ulang dan atmosfer penelitian yang jujur harus ditingkatkan.
2. Oportunisme Instansi
Singkat saja: universitas menjadikan penelitian sebagai alat pencitraan. Penelitian hanya diposisikan sebagai produk klaim, “kampus riset inovasi terbaik”, “kampus peneliti terbaik”, “kampus dengan publikasi terbanyak”, dan produk-produk citra kuantitatif lainnya.
Padahal, tujuan penelitian itu mulia banget lho, “Untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah, serta memberikan pertimbangan pada pembuat kebijakan dalam field tertentu” (Creswell, 2016)5.
Bagaimana masalah bisa selesai bila proses investigasinya tidak jujur? Bagaimana bisa jadi solusi bila penelitian tujuannya untuk mendongkrak citra kampus? Lebih parah lagi, bagaimana kebijakan bisa diambil dengan benar bila landasannya adalah produk ilmiah yang manipulatif dan tipu-tipu?
Ini adalah kritik kecil untuk semua kampus di Indonesia, bukan hanya yang disebutkan RI2.
3. Oportunisme Peneliti
Di balik penelitian yang Scopus, ada sedikit kenikmatan fulus.
Simpel saja: peneliti publikasi, peneliti dapat uang. Nah, kalau peneliti butuh uang, ya tinggal publikasi. Nggak sesimpel itu sih memang. Tapi kenyataanya memang ada oknum-oknum dosen yang menjadikan penelitian sebagai ajang cari cuan tambahan.
Motif penelitian sih masih sama: menyelesaikan masalah [sendiri]. Uang memang masalah semua orang, termasuk dosen, mahasiswa dan semua peneliti. Mereka juga manusia, butuh mengisi perut dan mengisi “banksaku”. Tapi nggak boleh juga dong kalau dinormalisasikan.
Kalau meneliti hanya jadi ajang pencairan uang, suram betul masa depan penelitian dan publikasi kita? Inilah pentingnya iklim penelitian yang jujur. Penelitian yang tidak hanya fokus pada novelty, tapi juga honestly.
Note: Jangan salah dulu ya, uang itu wajib ada dan penting banget dalam penelitian. Tanpa uang penelitian bahkan tidak bisa berjalan. Tapi kalau tujuan utamanya adalah uang, ya salah!
Semua harus dimulai pada diri pribadi individu. Peneliti dan dosen perlu memberikan contoh yang benar pada anak didiknya. Sebab sering kali pelaku manipulator penelitian bukan karena motif uang, tapi karena mereka tidak paham bagaimana penelitian seharusnya dilakukan. Mereka peneliti pemula hanya perlu bimbingan, masukan, dan arahan yang baik, bijak, dan solutif.
Waktunya Berbenah!
Adanya RI2 menjadi bukti bahwa masih ada seseorang yang ingin mengembalikan marwah penelitian pada tempatnya—tempat yang mulia di singgasana ilmu pengetahuan. Niat yang baik ini harus disambut dengan baik.
Kira harus melakukan refleksi, meninjau ulang regulasi, dan kembali merefresh iklim penelitian yang berintegritas. Pondasi utamanya adalah kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas. Yuk kita lakukan, mari kita songsong hasil-hasil penelitian yang berdampak dan bermanfaat untuk masyarakat di masa depan!
Referensi
- Armond, A. C. V., Cobey, K. D., & Moher, D. (2024). Research Integrity definitions and challenges. Journal of clinical epidemiology, 171, 111367. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2024.111367 ↩︎
- Van Noorden R. (2023). More than 10,000 research papers were retracted in 2023 – a new record. Nature, 624(7992), 479–481. https://doi.org/10.1038/d41586-023-03974-8 ↩︎
- Begley, C. G., Buchan, A. M., & Dirnagl, U. (2015). Robust research: Institutions must do their part for reproducibility. Nature, 525(7567), 25–27. https://doi.org/10.1038/525025a ↩︎
- Conroy, Gemma (2019). The 7 deadly sins of research. Nature News. https://www.nature.com/nature-index/news/the-seven-deadly-sins-of-research ↩︎
- Creswell, J. W. (2016). Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitataif & Kuantitatif (4th ed.). Pustaka Belajar ↩︎





